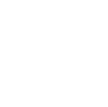BERFIKIR MANHAJI DAN ‘IRFANI Mempertemukan Pemikiran Substantif Kulliyyat dan Formal Juziyyat
Dibaca: 12985
Penulis :
BERFIKIR MANHAJI DAN ‘IRFANI
Mempertemukan Pemikiran Substantif Kulliyyat
dan Formal Juziyyat
Ayat Dimyati
Absrtak
Islam yang memiliki cita-cita rahmatan li al-‘âlamîn tidak mungkin tercapai dalam kehidupan ini kecuali dengan berfikir dan bertindak secara manhaji dan ‘irfani. Berfikir manhaji adalah berfikir tuntas dan komprehensif dari awal sampai akhir; dari zhahir sampai bathin, bahkan dari perseorangan sampai kolektif. Cara berfikir ini memiliki ciri komprehensif dari pemikiran awal sampai pencapaian tujuan akhir; komit-men yang jelas terhadap instrumen-instrumen formal yang perlu dilalui; perumusan sasaran yang perlu pada setiap instru-men formal; dan tujuan akhir merupakan kumulasi dari penca-paian setiap sasaran dalam instrumen formal.
Adapun berfikir ‘irfani adalah pengetahuan tentang sesuatu melalui proses berfikir mendalam dan sistemik untuk memper-oleh atsar dari buah fikir dan tindakannya itu. Cara berfikir ini memiliki ciri khas substantif; aspek batin dari setiap aturan formal sangat diperhatikan untuk membangun spirit; dan mengatur setiap aturan formal agar seimbang dengan capaian batinnya.
Langkah yang harus ditempuh untuk menuju pemikiran manhaji dan ‘irfani adalah dengan mengevaluasi berbagai hal yang berkaitan dengan keberagaman baik perorangan maupun jamaah. Beberapa pertanyaan sebagai bahan evaluasi tersebut meliputi: (1) sudahkah membaca teks suci keagamaan dan konteks lingkungan yang sedang terjadi; (2) sudahkah memak-nai keduanya itu secara seksama; (3) sudahkah memahami hubungan-hubungan di antara keduanya itu dengan teliti dan benar; (4) mampukah berdialog dengan keduanya dimana posisi diri dan umat dalam tuntutuan teks dan konteks; (5) sudahkah bersikap sesusai dengan tuntutuan yang dikehendaki keduanya; dan (6) bisakah berperilaku seirama dengan sikap yang dikehendaki oleh predikat kemuliaan sebagai makhluk Allah paling mulia.
Kata-kata Kunci:
Manhaji, ‘Irfani, Teks, Konteks
A. Pendahuluan.
Islam tidak hanya merupakan agama dalam idealitas penganutnya, melainkan juga dalam realitas kehidupan, bahkan kehidupan yang menjadi cita-citanya itu merambah keluar, tidak hanya bagi lingkungan para penganutnya.[1] Ungkapan cita-cita tersebut dikandung dalam Q.S. al-Anbiyâ [21] ayat 107: wa mâ arsalnâka illâ rahmatan li al-‘âlamîn.[2] Realitas kehidupan sekarang ini, tidak demikian; bahkan, umat Islam sering menjadi sasaran tudingan yang tidak layak bagi umat yang beragama apapun. Hal ini merupakan cambuk untuk lebih berintrospeksi dan mengevaluasi berbagai hal keberagamaan umat dan terutama para pimpinannya. Introspeksi dan evaluasi keberagamaan ini, perlu segera diper-hatikan bersama untuk mengeluarkan umat dari berbagai problema kehidupan yang dihadapinya.
Berbagai usaha untuk mencari jalan keluar dari berbagai problema itu, telah dilakukan oleh berbagai ahli dalam ber-bagai bidang keilmuan dan profesi, sejak dahulu sampai sekarang. Secara husn al-zhann, baik mereka yang berfikiran “liberal dan modern”, maupun yang berfikir “konservatif dan tradisional”,[3] sebaiknya dicarikan titik temu disertai hati yang jernih, daripada menyampaikan berbagai lontaran bernada permusuhan. Karena itu, dalam tulisan ini, tidak ada maksud untuk memihak kepada salah satu alur pemikiran dan amaliah keislaman tertentu, tetapi berusaha mencari titik temu di antara kedua alur pemikiran dan amaliah yang berbeda itu. Bahkan, kedua pemikiran dan amaliah itu dipertimbangkan, sebagai investasi besar bagi kokohnya ‘amal Islami yang relevan dan antisipasi berbagai kebutuhan dan tuntutan zamannya secara baik dan benar.
Ada tiga standar, baik bagi mereka yang berfikiran liberal maupun konservatif yang mengacu pada pencapaian cita-cita dan kesempurnaan ajaran Islam, yaitu: 1) keikhlasan, bahwa berfikir bebas itu merupakan anugrah Allah SWT; 2) memper-kokoh nilai insaniyah dalam bertindak, baik perorangan mau-pun kolektif; dan 3) membuka wawasan bagi perkembangan dan kemajuan umat, sebagai watak dari kehidupan di dunia ini. Ketiga hal tersebut, merupakan satu kesatuan yang tak terpi-sah. Kemajuan peradaban diperoleh dalam landasan kemanu-siaan universal yang kokoh; kemanusiaan berada dalam keikh-lasan individual yang sangat spesifik yang mengacu hanya pengabdian kepada Tuhan.
Tuhan yang dimaksud, sebagaimana yang diisyaratkan Q.S. al-Hadid: 3, yaitu: Dia Yang Awal dan Yang Akhir; dan Dia Yang Zhahir dan Yang Bathin.[4] Secara empiris formal da-lam kehidupan umat, pemaknaan “Yang Awal”, adalah dengan pembacaan “basmalah” dalam mengawali setiap perbuatan. Sedangkan pemaknaan “Yang Akhir”, adalah pembacaan “hamdalah” ketika selesai melakukan perbuatan. Pemaknaan seperti ini sah juga, walaupun tidak biasa orang-orang meng-ambil landasan perbuatannya langsung dengan ayat itu, tetapi menggunakan dalil juz’iy atau juz’iyyat, seperti hadis: kullu amrin dzî bâlin la yubda’u bi bismillah fa huwa aqtha‘ (setiap urusan yang tidak dimulai dengan mengucap bismillah al-Rahmân al-Rahîm, maka urusan itu adalah terputus). Landasan umum bagi pemaknaan seperti itu, bisa juga mengacu pada Q.S. al-‘Alaq: 1; iqra’ bi ismi rabbika al-ladzî khalaq. Demi-kian juga pemaknaan “Yang Zhahir” dan “Yang Bathin”. Yang zhahir, digunakan sebagai landasan keberagamaan kelompok orang-orang yang berfikiran formal (fuqaha), di samping argumen khususnya, yaitu hadis Nabi SAW: Nahnu nahkumu bi al-zhawâhir wa Allâhu yahkumu bi al-sarâir. Sedangkan yang batin, digunakan sebagai landasan keberaga-maan kelompok batiniyah (mutashawwifin). Pola pemikiran keislaman parsialitas juz’iyyat dan pada wilayah instrumental ini, telah melahirkan kepribadian muslim tidak utuh dan tidak istiqamah (split personality), apalagi dalam kontek kehidupan global sekarang yang sangat membutuhkan kesabaran, keta-wakkalan tinggi dan kebersamaan.
Berfikir manhaji yang dimaksudkan dalam tulisan ini, adalah berfikir tuntas dan komprehenshif; dari awal sampai akhir, dari zhahir sampai batin, bahkan juga dari perseorangan sampai kolektif.[5] Bila Q.S. al-Hadid: 3, dipahami seperti itu, maka di antara fase awal dan fase akhir itu, terdapat sejumlah instrumen/aturan formal yang perlu dilakukan. Jika instrumen-instrumen tersebut diperhatikan secara mendalam, akan meng-antarkan pada bagian akhirnya. Demikian pula instrumen-instrumen itu perlu ada, di antara zhahir dan batin-nya, pribadi (fard) dan kolektif (jama‘ah). Dengan demikian, agar umat Islam memperoleh kehidupan seimbang (wasatha), tinggi mar-tabat (ya’lu wa lâ yu’la ‘alayh) dan umat yang paling baik (khaira ummah), adalah menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab perorangan atau kelompok tertentu. Instrumen-instrumen tersebut, adalah tuntunan praktis syari‘ah yang sarat dengan muatan akhlak karimah. Namun perlu dicatat, pada tatanan implementasi, baik pada fase awal (berfikir atau bertindak) maupun fase akhirnya dari setiap tuntunan praktis syari’at itu, adalah mengandung muatan aspek zhahir maupun aspek batinnya secara bersamaan. Instrumen zhahir bisa berbeda di antara seseorang dengan yang lainnya. Perbedaan aspek zhahir itu bisa terjadi di seputar pengambilan dalil juz’iy yang berbeda-beda, atau dalilnya sama tetapi interpretasinya berbeda. Berdasarkan pemikiran manhaji dalil-dalil juz’iy yang berbeda itu, diposisikan sama; tetapi instrumen batinnya perlu sama, yaitu keikhlasan. Hal ini, karena menyangkut sasaran akhir yang dituju adalah sama juga, yaitu: secara vertikal ridla Allah SWT dan secara horizontal rahmatan li al-‘âlamîn.
‘Irfaniyang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah penge-tahuan tentang sesuatu melalui proses berfikir mendalam dan sistemik untuk memperoleh atsar dari buah fikir dan tin-dakannya itu.[6] Karena yang difikirkan itu adalah sesuatu yang terbingkai dalam ayat-ayat Tuhan, maka akibat yang diper-olehnya, hanya pembuktian atas ke-Mahabesaran Allah SWT; dan akibat dari tindakannya, hanya kebaikan untuk semua. Berfikir untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu (idrak), adalah berfikir detail, sistimatis dan terintegrasi, baik terhadap aturan-aturan formal yang bersifat instrumental, maupun terhadap konteks yang dihadapi secara bersamaan. Dikatakan “sistemik”, karena dilakukan secara terencana, terprogram dan terarah dari awal sampai akhir, dari hal-hal yang detail sampai besarannya. “Atsar” dimaksudkan agar produk berfikir itu tidak terhenti pada pemikiran personal individual, tetapi bermanfaat dan teraplikasi pada kehidupan pribadi dan kolektifnya, baik lahir maupun batin menuju tingkatan yang paling baik dan sempurna[7]. Al-Jabiri (Bunyah al-‘Aql: 1993/251) menjelaskan makna al-‘Irfan adalah al-ma’rifah, yaitu pengetahuan yang diperoleh di dalam hati melalui kasyf atau ilham (intuisi). Ia berbeda dengan pengeta-huan yang diperoleh melalui usaha indra dan rasio. Untuk hal ini, ia mengutif pernyataan Dzu al-Nun al-Mishri (w 245), yang membagi sifat pengetahuan kepada tiga sifat: 1) Pengetahuan tentang tauhid; diperuntukkan bagi pada umum-nya orang-orang mu’min yang ikhlas; 2) pengetahuan berargu-mentatif dan berpenjelasan, diperuntukkan bagi para filosuf dan ulama yang ikhlas; dan 3) pengetahuan tentang kesatuan penciptaan bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas dan yang bersaksi di dalam hatinya sampai tampak jelas kebenaran itu di hadapan-nya. Namun, yang dimaksud ‘Irfani di sini adalah berpangkal dari teks nash, kemudian dikaji secara mendalam untuk mencari aspek substantifnya. Pemakaian kaidah-kaidah kebahasaan dan kaidah-kaidah kealaman yang bersifat makro, merupakan satu kesatuan alat ukur yang tidak bisa diabaikan dan dipisahkan.
Karena itu, cita-cita rahmatan li al-‘âlamîn, tidak mungkin bisa dicapai dalam kehidupan ini, kecuali dengan berfikir dan bertindak secara manhaji dan ‘irfani dalam pengertian seba-gaimana yang telah diajukan di muka dalam suasana suasana kemerdekaan (tidak terbingkai dan tersekat oleh fikiran siapa pun) dan kesungguhan (serius dan kerja keras). [8]
Kemudian pada tatanan implementasi perlu ada bingkai akhlak karimah yang mengandung tiga unsur: 1) hikmah, yaitu ketepatan dalam pemberlakuan ilmu pengetahuan dan amal, dengan sasaran-sasaran kebenaran yang akan dicapai; 2)‘iffah, yaitu pengendalian diri dari sifat arogansi dan berbagai kepentingan dan pengaruh luar yang buruk) ; dan 3) syaja’ah, yaitu keberanian menawarkan sesuatu yang baru, guna perbaikan hidup dan kehidupan. Untuk itu, integrasi ketiga potensi insaniyah yang dimiliki setiap orang itu adalah sangat diperlukan, yaitu: indra (Hawas), hati (Qalb) dan nurani (Lubb).
B. Problema Berfikir Manhaji dan ‘Irfani.
Dalam agama yang diturunkan Allah itu, sebagaimana diisyaratkan Q.S. al-Maidah: 48, mengandung dua muatan, yaitu syir‘ah dan minhaj. Pada tatanan empiris implementasipola syir‘ah yang lebih tampak sebagai ukuran pembenaran keagamaan umat. Syir‘ah, sebagaimana dipahami ‘Ali al-Sayis adalah hukm yata’allaqu bihi af‘âl al-mukallaf. Ia bersifat formal dan spesifik. Di antara kedua muatan itu, secara historis keilmuan di kalangan umat Islam, pola syir‘ah yang memperoleh respon sehingga berkembang pesat.
Ilmu Ushûl Fiqh yang diklaim sebagai metodologi penaf-siran hukum Islam, wilayah kajiannya lebih menekankan pada kaidah-kaidah kebahasaan secara formal, zhahir dan spesifik, sehingga hasil kesimpulannya pun bersifat formal, zhahir dan spesifik dan terbatas pada pencarian dalil-dalil, kaifiyah dan alat yang dipakainya. Sekalipun dibahas juga aspek maqâsid al-syarî‘ah (makna rasional: motif dan tujuan, illah al-hukm dan hikmah al-tasyrî‘) berikut konsep tanggung jawab kolektif (kifa'iy) dalam pelaksanaan hukum, namun tidak berlanjut pada tatanan praktisnya yang berada pada wilayah studi fiqh. Sementara itu, tidak ada wilayah praktis, baik ibadah ritual yang sangat personal, terutama mu‘âmalah dunyâwiyah, yang bisa lepas dari keterkaitannya dengan hukum alam dan ling-kungan (konteks). Penyelesaian persoalan publik lebih awal dilakukan, merupakan hal yang sangat strategis, untuk pembi-naan keumatan. Hal ini karena urusan privat akan mudah terkondisikan dengan baik, oleh karena kondisi publiknya telah baik lebih awal, tidak sebaliknya. Karena itu, aspek kifa’iy dan maqasid ini perlu lebih banyak ditawarkan guna penyelesaian berbagai persoalan publik ini.[9] Hal ini pula yang menjadi sasaran dari cita-cita agama Islam, yaitu mewujudkan perbaikan hidup di alam ini dengan rumusan: li shalâh al-‘ibâdi dunyâhum wa ukhrâhum atau rahmatan li al-‘âlamîn. Karena itu pula studi teks--guna mewujudkan ketaatan secara per-sonal--, perlu dibantu oleh studi konteks yang terdapat di alam sekitarnya agar kesadaran sosial dan pemeliharaan lingkungan bisa diciptakan secara bersamaan. Pola studi konteks ini, adalah mencari hubungan-hubungan di antara semua realitas dan hakikat-hakikat hubungan itu. [10]
Secara keilmuan, hukum alam dan lingkungan dimaksud, telah dikembangkan melalui studi IPTEK yang banyak diperhatikan oleh dunia Barat dengan begitu pesat dan detail. Secara empirik, melalui kajian IPTEK ini, perbaikan hidup dalam wujud kesejahtraan ekonomi, demikian maju dengan pesat, namun aspek moral semakin hari semakin merosot. Karena itu logis, bila penawaran kajian-kajian keislaman sekarang ini, oleh sebagian kelompok orang, lebih banyak bersifat komprehenshif. Hal ini ditawarkan guna menumbuh-kan kesadaran moral besar (akhlak ‘uzhma).
Sementara itu pula kajian Ushûl al-Fiqh sebagai andalan metodologi penggalian hukum Islam, lebih pada wilayah teks-teks syari‘ah, terpisah jauh dari konteks. Hanya sebagian kecil saja yang menyangkut konteks ini, dibahas dalam Ilmu Ushûl Fiqh, yaitu aspek subjek hukum, dengan konsep ahliyah al-wujub dan ahliyah al-ada.[11] Karena itu, pengembangan meto-dologi penetapan hukum yang diperlukan sekarang ini, adalah dengan mengintegrasikan kedua bidang ini--teks dan konteks-, terutama yang menyangkut kaidah-kaidah dasar kedua bidang kajian itu. Hal ini merupakan kebutuhan umat yang sangat mendesak.[12] Di samping itu, aspek-aspek maqashid dan kifa’iy ini, perlu dikaji juga secara seimbang dengan aspek-aspek individual (‘ainiy)-nya yang ditemukan dalam setiap rumusan teks normatif keagamaan dan konteksnya.[13] Kedua hal itu, perlu dipertemukan dalam sebuah kesatuan kerangka metodo-logi (unity of methodology), kemudian ditawarkan melalui konvensi para pakar. Usaha tersebut, merupakan kelanjutan materi kajian fase sebelumnya yang lebih bersifat spesifik.
Problema yang dihadapi untuk bisa memasuki unity of methodology ini, adalah terkait dengan kerangka fikir peru-musan keilmuan yang dipakai sekarang; baik rumpun keilmuan naqliyyah, maupun rumpun keilmuan ‘aqliyyah,[14] yaitu mengacu pada konsep Syllogisme Cathegory Aristo.[15] Konsep ini, ditransfer menjadi kerangka metodologi Ushûl al-Fiqh oleh Imam al-Syafi’i dalam al-Risalah--yang sampai sekarang kerangka tersebut belum ada perubahan--, yaitu: premis mayor (muqaddimah qubra), premis minor (muqaddi-mah shughra) dan konklusi (natijah). Kerangka fikir ini sangat tampak dalam keputusan-keputusan hukum al-Syafi’i, walau-pun ia sendiri tidak langsung menyatakan hal tersebut dalam kitabnya itu. Implikasi pemakaian kerangka pemikiran ini terhadap kehidupan umat, mengandung dua hal: positif dan negatif. Aspek positifnya, karena dengannya akan lebih mem-percepat pengembangan keilmuan, yang objek penelitiannya tidak hanya pada benda pisik besar, tetapi sampai pada wilayah mikro organis sekalipun. Hal ini sudah terbukti dikembangkan oleh Dunia Barat dengan prestasi IPTEK-nya dan di dunia Islam dengan prestasinya pada masa yang lalu, terutama dalam bidang hukum Islam (fiqh Islam). Melalui pola itu, studi keilmuan sangat detail, bahkan sangat spesifik. Aspek negatifnya, adalah parsialitas keilmuan tam-pak sekali, yang satu semakin sangat jauh dari yang lainnya. Implikasi lebih jauhnya adalah ke-aku-an/individualitas pada pribadi orang yang berilmu itu lebih menonjol, daripada tanggung jawab pemanfaatan ilmunya itu bagi orang banyak. Problema ini terjadi dalam wilayah implementasinya sekarang ini, baik bagi mereka yang mengacu pada pola pemikiran Barat, maupun mereka yang mengacu pada pola pemikiran Timur Islam.
Kebutuhan terhadap bangunan kesatuan kerangka meto-dologi (teks dan konteks), demikian pula studi terhadap teks-teks keagamaan, perlu dibangun relevansinya dengan tuntutan perkembangan dan beban problema kehidupan yang dialami sekarang. Bangunan metodologi tersebut lebih bersifat integral dan konperhenshif, namun tidak terpisah dengan wilayah praktisnya yang sangat spesifik. Kaidah-kaidah universal ber-fungsi memayungi kaidah-kaidah spesifiknya. Seperti dalam memasangkan halal bayyin dan haram bayyin bagi sebuah makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat, seperti: roti, baso, biscuit, daging, dll., diperlukan para ahli yang bukan saja ahli hukum Islam yang mendalami teks-teks Al-Qur’an dan al-Hadits serta berbagai referensi hukum Islam secara detail, tetapi diperlukan juga kehadiran para pakar kimia, ahli kesehatan dan ahli gizi yang secara detail pula pengetahuan mereka di bidangnya itu. Rumusan Q.S. al-Maidah: 1; wa uhillat lakum bahîmah al-an‘âm (dan dihalalkan bagi kamu sekalian hewan ternak), adalah merupakan konsep global kehalalan hewan ternak, seperti kambing, sapi, dll. Namun, apabila daging kambing itu, sudah dimasak dengan digoreng dan dibumbui, sebagaimana terdapat di rumah-rumah makan, maka kehalalannya perlu di-tabayyun-kan lagi sampai detail. Pengungkapan kembali kedetailan makanan daging tersebut, diperlukan keahlian khusus dalam bidang teknologi makanan, kesehatan dan gizi, dan tidak dicukupkan bersandar pada globalnya hukum halal hewan ternak itu. Dengan demikian, tuntutan ijtihad dalam kontek sekarang, lebih banyak dilakukan secara kolektif (ijtihad jama‘îy) daripada perse-orangan (ijtihad fardiy). Sementara materi studi keislaman yang menitikberatkan pada prestasi kolektif ini adalah sangat jarang. Hal tersebut, sebenarnya tidak perlu terjadi, karena agama Islam ini oleh para ahli dikatakan Islam aqîdah wa syarî‘ah, fard wa jamâ‘ah, dîn wa dawlah/nizhâm. Demikian pula, teks-teks nash, bila diperhatikan dengan cermat akan tampak keluasan kandungannya yang terbagi kepada tiga: Kulliyyat, Juz’iy dan Juz’iyyat; di bawahnya lagi adalahfar’iyyat.[16] Demikian pula ilmu kealaman (konteks) terbagi pula seperti empat klasifikasi itu.
Problema lainnya dalam memasuki cara berfikir manhaji dan ‘irfani adalah perumusan definisi atau ta’rif setiap aturan formal yang telah dirumuskan para ulama dalam literatur fiqh, kurang memenuhi syarat, bila dihubungkan dengan tingkat kemajuan masyarakat. Kekurangan tersebut terletak pada kurang menangkap berbagai problema yang terjadi dan kom-ponen sasaran dari masing-masing aturan formal itu tidak tampak jelas, apalagi bila dihubungkan dengan tujuan akhir dari keberagamaan itu. Beberapa contoh akan disajikan di sini, sbb.: definisi shalat, dalam Fiqh al-Sunnah karya Sayyid al-Sabiq, dirumuskan: ‘ibadatun al-latî tatadlammanu min aqwâlin wa af‘âlin makhshûshatin muftatahatun bi al-takbîr wa mukhtatamatun bi al-taslîm (Ibadah yang terhimpun dari berbagai perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali/dibuka dengan takbiratulihram dan diakhiri dengan salam). Dalam definisi shalat itu terlihat kekurangan aspek batinnya dan sasaran-saran antara dari shalat itu. Padahal tujuan shalat secara jelas tertera dalan Al-Qur’an, baik secara individual maupun secara komunal.[17] Apalagi tujuan akhir dari hakikat shalat itu yang ingin dicapainya, maka penegasan sasaran tentang shalat dalam ta’rifnya itu perlu ditegaskan secara tersurat. Seperti tambahan ungkapan setelah ta’rif itu: li ittikhâdzi al-sakînati fi al-nafsi wa li intihâi al-fâhisyati wa al-munkari fi ijtimâ‘ihim. (agar jiwa menjadi tenang dan masyarakat terhindar dari perbuatan keji dan munkar). Shaum di definisikan: imsâkun ‘an mufaththiratin bi niyyatin makhshûshatin min jamî‘in al-nahâr qabil li al-shawm (menahan diri dari segala yang membatalkan dengan niyat khusus, selama siang hari yang menerima untuk dipuasai). Sasaran shaum adalah ketaqwaan (la‘allakum tattaqûn), pengendalian diri (junnah) dengan kesabaran (al-shawm nishf al-shabr) dan kesucian (thuhratan li al-shâim). Sasaran-saran tersebut tertulis formal baik dalam Al-Qur’an maupun dalam hadits Nabi SAW. Demikian juga rekonstruksi dalam ta’rif hukum yang terrumuskan dalam Ilmu Ushûl al-Fiqh. Dalam definisi itu disebutkan bahwa objek hukum adalah orang-orang mukallaf. Hal ini memberikan batasan bahwa bagi yang bukan mukallaf tidak bisa terkena hukum. Definisi tersebut kurang mengakses perkembangan penguasaan aset-aset perekonomi-an, bahwa sekarang ini wilayah perekonomian itu, lebih banyak dikuasai lembaga-lembaga secara korporasi, tidak lagi personal, seperti negara tertentu atau daerah tertentu atau lembaga tertentu, yang sementara masih terdapat Negara, daerah dan lembaga sosial lain yang termasuk miskin. Bila kondisinya tetap demikian, karena dipandang definisi itu merupakan doktrin keagamaan yang tetap, maka dalam kehidupan sosial akan mengalami ketimpangan berat, dimana solidaritas tidak lagi tercipta. Rekonstruksi ta’rif-ta’rif keaga-maan formal ini diadakan agar terjadi perubahan sikaf keber-agaam umat secara merata, setelah melewati sistem pengajaran dengan materi ajar yang baru. Seperti kasus yang terjadi dalam kewajiban zakat--oleh karena lembaga itu dipandang bukan mukallaf--, maka zakat lembaga belum bisa diterima umat secara merata. Karena itu, rekonstruksi definisi hukum dengan tambahan kalimat syakhshiyyan aw hukmiyyan, fardan wa jamâ’atan (personal atau lembaga, seorang diri atau kolektif), merupakan satu kebutuhan yang tidak terelakan lagi. Dua padanan kalimat itu diletakkan setelah ungkapan: yata’allaqu bihi af‘âl al-mukallaf. Penambahan sasaran/tujuan dari hukum itu ke dalam ta’rifnya juga, tidak disalahkan, seperti ungkapan al-ladzî tashilu al-mashâlih al-‘ammah.[18] Hal ini, karena perumusan ta’rif hukum yang telah ada itu sendiri, mengalami perkembangan sampai empat tahapan, dan kelima tahapannya yang ditawarkan dalam tulisan ini.
Satu hal lagi yang bisa dipandang suatu problema adalah dimensi sikap para pemangku keilmuan itu, demikian juga para pemakainya. Bila aspek sikap akademik (akhlak karimah) dari setiap pemangku keilmuan dan para pemakainya kurang diperhatikan, maka manfaat dari ilmunya itu tidak akan maksimal, bahkan ada kemungkinan saling berjauhan.
Atas dasar problema di atas, kerangka metodologi dan amaliah dari setiap studi keislaman, dirumuskan sebagaimana kerangka berikut:
Tawhidullah
![]()
`Abd al-Rubûbiyyah `Abd al-Thâ'ah
(Perjanjian Ketuhanan) (Perjanjian Ketaatan)
|
|
|
Qawâ'id Khalqiyyah Qawâ'id Lughawiyyah

 (Kaidah Penciptaan) (Kaidah Kabahasaan)
(Kaidah Penciptaan) (Kaidah Kabahasaan)
![]()
Dalâil, Kaifiyah wa Adawat
(Dalil, Cara dan alat-alat)
Shillah bainahunna
( hubungan-hubungan )
Haqîqatuhunna
(Hakikat Hubungan)
![]()
al-Atsarah al-Mu'tabarah
|
|
al-Ghayah al-Mawshulah
C. Paradigma Kesatuan dan Epistimologi Pemikiran.
Ide kesatuan telah menjadi tradisi dalam khazanah inte-lektual Muslim, bukan hanya dalam wilayah keimanan dengan tawhidullah-nya, tetapi juga dalam dunia ilmu pengetahuan. Mempertemukan hubungan yang tepat di antara berbagai disiplin ilmu pengetahuan itu, merupakan obsesi para tokoh intelektual Muslim terkemuka dari teolog hingga filosof, dari sufi hingga sejarahwan, seperti al-Farabi, Al-Ghazali dan Quthb al-Din al-Syirazi (Pengt. Sayyed Hossen Nasr; dalam Osman Bakar , Hirarki Ilmu: 1992/11).[19]
Secara substantif fungsional, agama Islam merupakan pedoman/petunjuk bagi hidup dan kehidupan umatnya. Bila petunjuk itu diikutinya, maka sudah tentu akan mengantarkan mereka pada kehidupan yang lebih baik (khayra ummah) dalam berbagai aspeknya, dan terciptanya kesatuan umat (ummah wâhidah) di dunia maupun di akhirat. Bahkan posisi tersebut dinyatakan oleh Q.S. Ali ‘Imran 110, sebagai umat paling baik; dulu, sekarang, kapanpun dan di manapun.[20] Namun, dalam realitas umat Islam sekarang ini sedang dalam keterpurukan dalam berbagai bidang kehidupan dan terpecah dalam berbagai kelompok aliran. Bila demikian keadaannya, tentu terdapat masalah yang perlu segera dipecahkan. Diyakini benar, masalah tersebut bukan terletak pada sumber ajaran Islam, tetapi pada penerapan ajaran itu dalam wilayah kehidupan praktis yang senantiasa berubah-ubah. Kaidah menyatakan: al-nushush mutanahiyah, al-waqi’ ghair mutanahiyah (nash itu telah berakhir/terhenti, sedangkan peristiwa terus berubah/ tidak pernah berakhir). Karena itu ukuran kehidupan praktis, didasarkan pada pola fikir dan kaidah interpretasi terhadap sumber ajaran itu. Bila pola fikir dan kaidah interpretasi terhadap nash suci, tidak berkembang--sementara kehidupan terus berubah--, maka masalah keberaga-maan semakin lama akan semakin berat dan komplek.[21]
Maka dari itu, gerakan pembaharuan pemikiran terhadap ajaran agama yang bisa mengakses persoalan-persoalan keu-matan, perlu terus berkembang juga. Kata umat dalam term umat Islam merupakan satu konsep abadi yang tidak ditemu-kan pada umat/masyarakat selainnya. Di dunia Barat terdapat konsep kesatuan masyarakat, tetapi lebih bernuansa insidental yang berwujud dalam komunitas ekonomi, politik dan profesi yang jauh berbeda dengan konsep umat dalam agama Islam (Cf. Isma’il Razi al-Faruqi, Tauhid: 106-134). Ia dibangun di atas dasar sistem keimanan yang kokoh dan kuat (‘urwa al-wutsqa), yaitu tawhidullah dan amar ma‘rûf wa nahyi munkar. Keyakinan yang kokoh dan kuat itu dicatat dalam ikatan perjanjian yang kokoh pula yang dikatakan ‘ahd al-mîtsaq. Perjanjian ini berlangsung, ketika Tuhan bertanya kepada para arwah bani Adam--sebelum lahir menyatu dengan jasad di dunia--, tentang diri-Nya. Q.S.al-A’raf: 172; a lastu bi rabbi-kum? qâlû balâ syahidnâ (bukankah Aku ini, Rabb kamu sekalian? Mereka para arwah menjawab: benar! kami ber-saksi).
Ayat itu menunjukkan, bahwa semua manusia -- tanpa kecuali -- beragama atau tidak, durhaka atau salih, telah mengenali persaksian atas Rububiyah ini sejak dari masa awal sekali. Fazlur Rahman (Tema Pokok, trj. Anas M: 1980/26) menyebut perjanjian itu sebagai ikrar primordial.[22] Istilah yang dipakai bagi perjanjian rububiyyah dalam tulisan ini, dikatakan Al-‘Ahd al-Rububiyyah, berikutnya disingkat dengan AR. AR ini dimaksudkan adalah perjanjian pengakuan hanya Tuhan sebagai pencipta setiap diri manusia, alam dan makhluk lainnya. Dia yang mengatur, membina dan memeli-hara semua yang ada di alam raya ini. Semua makhluk Allah mentaati segala perintah-Nya, tanpa ada pengingkaran. Namun, di antara makhluk Allah yang bernama manusia itu, terdapat sebagiannya yang tidak menyadari perjanjian itu.[23]
Oleh karena itu, bila Tuhan menuntut manusia untuk men-taati-Nya, baik terhadap perintah-perintah-Nya untuk dilak-sanakan, maupun terhadap larangan-Nya untuk dijauhi, serta memperhatikan pula segala yang diizinkan-Nya, adalah logis sekali. Ikatan perjanjian keta’atan itu, dikatakan: ‘Ahd al-Tha’ah--berikutnya disingkat denganATh-- (Cf. Wahbah Zuhayli, al-Tafsîr al-Munîr: V-VI/102-103; Cf. Fazlur Rahman, Ibid.: 26-53).
BaikARmaupun ATH, perlu dirumuskan kriterianya masing-masing. Kriteria tersebut disepakati bersama dan merupakan acuan bagi semua orang yang ada dibelakangnya. Hal ini sudah dirumuskan oleh para ahli, hanya tinggal mem-pertemukan di antara keduanya itu. Kriteria AR ditemukan dalam kaidah-kaidah penciptaan (al-Qawa’id al-Khalqiyyah)--berikutnya disingkat QKh--, sebagai objek studi kealaman yang mengacu pada hukum-hukum sunnatullah.[24] Sedangkan kriteria ATh ditemukan dalam kaidah-kaidah studi risalah kewahyuan yang terkandung dalam teks kitab suci dan hadis nabawi (al-Qawa’id al-Lughawiyyah)--berikutnya disingkat QL--.[25] Kedua kaidah besar ini, masing-masing memiliki kaidah-kaidah mayor dan kaidah-kaidah minornya.[26] Kaidah-kaidah tersebut dipakai dalam rangka oprasionalisasinya, bahkan sampai pada tahapan oprasionalisasi paling detail. Perumusan kaidah-kaidah ini penting, bagi pengembangan secara spesifik dari masing-masing bidang keilmuan tersebut. Langkah ini sudah dilakukan para ilmuan terdahulu; hanya di antara kedua bidang itu, masih tersajikan secara terpisah. Penyajian secara terpisah ini, berimplikasi pada kurang bisa diperoleh manfaat besar dan optimal dari kemajuan ilmu pengetahuan itu, bagi kehidupan bersama umat manusia. Untuk bisa membangun manfaat besar dari kemajuan ilmu itu bagi kehidupan umat di dunia ini, diperlukan bangun etika/ moral yang melekat baik pada para pengembang ilmu itu, maupun pada para penggunanya.[27] Bangunan etika dan moralitas itu, bersifat substantif, mendasar dan melekat, tidak terpisah pada bagian-bagian aktivitas baik perorangan maupun kolektif tertentu; sekecil apapun keberadaan aktivitas itu. Bila tidak bisa menjangkau manfaat bagi kehidupan kolektif secara menyeluruh, maka bagaimana memaknai maksud dari cita-cita kehidupan rahmatan li al-‘âlamîn itu, padahal makna itu yang dimaksudnya. Dengan demikian, bangunan metodologi yang diinginkan adalah yang berangkat dari substantif, prinsif dasar, melalui instrumen-instrumen formal, menuju substantif dan prinsif dasar kembali.[28]
Gambaran hubungan nilai etika/moral besar yang melekat pada bagian-bagian aktivitas itu, sebagai berikut:
Ketuhanan
 |
![]() Peradaban Kemanusiaan
Peradaban Kemanusiaan
![]()

 Ketuhanan, kemanusiaan dan peradaban itu, merupakan nilai etika dan moral universal (grand morality/al-‘uzhma) yang membingkai setiap aktivitas dalam kehidupan, baik invidu maupun kolektif. Demikian juga etika dan moral menengah (middle morality/al-wustha) yang ada pada setiap tuntutan lokal dan komunitas, yang dikenal dengan tradisi kolektif yang bisa membangun moral kolektif. Sedangkan nilai etika/moral yang ada pada masing-masing individu sebagai maziyyah/ciri khasnya yang membedakan diri yang satu dengan diri yang lainnya, dikatakan etika dekat/bawah (low morality/al-adna). Ketiga cakupan etika itu yang satu dari yang lainnya tidak terpisahkan tetapi saling berhubungan dan saling mendukung, menuju satu kesatuan arah. Pewilayahan moral/akhlak ini sangat penting, terutama bagi pertanggungjawaban kepemimpinan.[29]
Ketuhanan, kemanusiaan dan peradaban itu, merupakan nilai etika dan moral universal (grand morality/al-‘uzhma) yang membingkai setiap aktivitas dalam kehidupan, baik invidu maupun kolektif. Demikian juga etika dan moral menengah (middle morality/al-wustha) yang ada pada setiap tuntutan lokal dan komunitas, yang dikenal dengan tradisi kolektif yang bisa membangun moral kolektif. Sedangkan nilai etika/moral yang ada pada masing-masing individu sebagai maziyyah/ciri khasnya yang membedakan diri yang satu dengan diri yang lainnya, dikatakan etika dekat/bawah (low morality/al-adna). Ketiga cakupan etika itu yang satu dari yang lainnya tidak terpisahkan tetapi saling berhubungan dan saling mendukung, menuju satu kesatuan arah. Pewilayahan moral/akhlak ini sangat penting, terutama bagi pertanggungjawaban kepemimpinan.[29]


![]() Pada tahap awal proses perumusan QKh dan QL itu sangat berbeda, karena berbeda objek dan pola studi di antara kedua-nya.[30] Namun, pada fase berikutnya, karena bingkaian etika/ moral di atas, berindikasikan hasil yang diperolehnya adalah sama, penciptaan kesadaran kolektif. QKh diproses melalui pencarian dan perkiraan secara filosofis, menuju kepastian hukum yang tetap, logis dan empiris. Sedangkan QL, diproses melalui kepastian kewahyuan dengan keimanan, berlanjut pada pencarian dan perkiraan secara filosofis untuk memperoleh kepastian secara logis dan empiris pula.[31] Point terakhir ini yang mengisyaratkan bahwa wahyu dan akal sehat tidak saling berlawanan, bahkan menunjukkan adanya satu kesatuan yang utuh. Dikatakan akal sehat, karena untuk bisa melahirkan sikap akademik dari para pemangku ilmu dan penggunanya pada tatanan empiris, hanyalah dengan penggunaan akal sehat (al-‘aql al-khâlish) ini. Akal sehat dimaksud tiada lain adalah al-lub (al-albâb, jamak) yang dalam term tulisan ini digunakan istilah nurani. Ia merupakan potensi dalam diri manusia, guna penumbuhan akhlak/moral seseorang pada wilayah praksisnya. Dalam dialog Nabi SAW dan ‘Ali ra., nurani ini dikatakan juga nafs yang memberikan pembenaran akhir bagi setiap masalah ijtihadiyah yang dipandang meragukan. Nabi SAW berkata kepada ‘Ali ra: istafti nafsak (mintalah kamu fatwa kepada hati/akal sehat mu). Nurani ini pula merupakan kekuatan moral yang memiliki daya dorong dan daya ikat di antara parsialitas keformalan dan juz’iyyat dengan kaidah-kaidah universal, filosofis dan kulliyyah –nya sebagaimana dikemukakan di atas.[32]
Pada tahap awal proses perumusan QKh dan QL itu sangat berbeda, karena berbeda objek dan pola studi di antara kedua-nya.[30] Namun, pada fase berikutnya, karena bingkaian etika/ moral di atas, berindikasikan hasil yang diperolehnya adalah sama, penciptaan kesadaran kolektif. QKh diproses melalui pencarian dan perkiraan secara filosofis, menuju kepastian hukum yang tetap, logis dan empiris. Sedangkan QL, diproses melalui kepastian kewahyuan dengan keimanan, berlanjut pada pencarian dan perkiraan secara filosofis untuk memperoleh kepastian secara logis dan empiris pula.[31] Point terakhir ini yang mengisyaratkan bahwa wahyu dan akal sehat tidak saling berlawanan, bahkan menunjukkan adanya satu kesatuan yang utuh. Dikatakan akal sehat, karena untuk bisa melahirkan sikap akademik dari para pemangku ilmu dan penggunanya pada tatanan empiris, hanyalah dengan penggunaan akal sehat (al-‘aql al-khâlish) ini. Akal sehat dimaksud tiada lain adalah al-lub (al-albâb, jamak) yang dalam term tulisan ini digunakan istilah nurani. Ia merupakan potensi dalam diri manusia, guna penumbuhan akhlak/moral seseorang pada wilayah praksisnya. Dalam dialog Nabi SAW dan ‘Ali ra., nurani ini dikatakan juga nafs yang memberikan pembenaran akhir bagi setiap masalah ijtihadiyah yang dipandang meragukan. Nabi SAW berkata kepada ‘Ali ra: istafti nafsak (mintalah kamu fatwa kepada hati/akal sehat mu). Nurani ini pula merupakan kekuatan moral yang memiliki daya dorong dan daya ikat di antara parsialitas keformalan dan juz’iyyat dengan kaidah-kaidah universal, filosofis dan kulliyyah –nya sebagaimana dikemukakan di atas.[32]
Semua konsep di atas, satu sama lain saling berhubungan secara simbiosis (timbal balik secara seimbang dan saling melengkapi). Ukuran kebenaran yang diproduk berdasarkan QL, relevan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam QKh, demikian sebaliknya. Tingkat hubungan yang seperti ini yang dikatakan Tauhid Ilmu (Cf. Isma’il Razi al-Faruqi, Tauhid; trj. Rahmani Astuti: 1995/40-47; Cf. Hendar Riyadi, edt. Tauhid Ilmu, MTPPI PWM Jawa Barat: 2000). Achmad Charris (Dimensi Etik.; dalam Pngt.: 2002/vi) menyebutkan bahwa keutuhan kebenaran adalah berarti hilangnya dikotomi antara kebenaran ilmiyah dengan kebenaran iman. Pertemuan itu diperoleh karena fungsi akal sehat pada setiap pemangku ilmu itu dalam tatanan aplikasinya. Hal ini karena, ilmu pengeta-huan yang didasarkan pada produk integrasi ketiga kekuatan dasar di atas, akan melahirkan aksi yang sebenarnya. Gam-baran ketiga kekuatan dasar itu, sebagai berikut:
Manusia
|
|
Indra Hati Nurani
 |
 |
Aktivitas
Aktivitas manusia yang ditunjukkan oleh gerakan-gerakan indranya, baru bisa dikatakan beretika/bermoral baik dan mulya, bila aktivitas itu didorong oleh dua potensi dasar lainnya yang ada di dalam diri manusia itu secara terintegrasi, yaitu hati baik dan nurani.[33] Mengintegrasikan ketiga potensi itu adalah sangat sulit, karena itu diperlukan kesungguhan dan kesabaran.[34] Hal tersebut diisyaratkan Q.S. al-Baqarah: 45; mintalah kamu sekalian pertolongan dengan bersabar dan bershalat/berdo’a, karena shalat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.
Konsep kesatuan pada wilayah subtansi ini, merupakan suatu paradigma yang akan dipakai dalam setiap pemikiran manhaji dan ‘irfani, baik dalam masalah pemikiran filosofis tentang ritual/ibadah, maupun dalam aktivitas empiris dalam bidang sosial, seni budaya, keilmuan, perorangan dan kelom-pok. Dan sekaligus pula sebagai landasan epistimologi kedua corak pemikiran itu secara terintegrasi.
D. Beberapa Langkah Praktis Menuju Pemikiran Manhaji dan ‘Irfani.
Bila pemikiran manhaji dan ‘irfani itu, sudah dipahami dan diterima sebagai acuan dalam berfikir keberagamaan, maka langkah pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin memasukinya adalah meng evaluasi berbagai hal yang berkaitan dengan keberagamaan, baik perorangan atau umat pada umumnya. Beberapa pertanyaan sebagai bahan evaluasi tersebut, meliputi: 1) Sudahkah kita membaca teks suci keagamaan dan konteks lingkungan yang sedang terjadi; 2) sudahkah kita memaknai keduanya itu, secara seksama; 3) sudahkah kita memahami hubungan-hubungan di antara keduanya itu, dengan teliti dan benar; 4) mampukah kita berdialog dengan keduanya, dimana posisi diri dan umat dalam tuntutan teks dan konteks itu; 5) sudahkah kita bersikap sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki keduanya; dan 6) bisakah kita sebagai makhluk Allah paling mulya, berprilaku seirama dengan sikap yang dikehendaki oleh predikat kemulyaan itu.[35]
Keenam pertanyaan itu, bisa dikatakan sederhana dan bisa juga dikatakan rumit dan berat. Pada umumnya orang-orang, sekalipun mereka itu dipandang ahli membaca dan sudah pandai memaknai, namun merasa berat ketika memasuki point ke 3 nya. Point ke 4, ke 5 dan ke 6 akan terasa lebih sulit lagi. Keenam pertanyaan itu diperlukan, guna merespon keterting-galan dan guna memenuhi keseimbangan di antara keilmuan yang diperoleh seseorang dengan pengalaman keberagamaan (religious experience) nya. Sehingga, tahap berikutnya tidak terjadi split personality, sebagaimana diisyaratkan oleh Q.S. al-Baqarah: 34; Apakah kamu sekalian menyuruh manusia, untuk senantiasa melakukan berbagai kebaikan, padahal kamu sekalian melupakan diri kamu (atas kebaikan itu); sedangkan kamu sekalian termasuk orang-orang yang membaca al-kitab; apakah kamu tidak berfikir.
Syaikh Hasan al-Banna (Muqaddamah fi ‘Ilm al-Tafsir: 30) menjawab pertanyaan salah seorang muridnya tentang tafsir Al-Qur’an yang baik dan cara memahami (thuruq al-fahm) kitab Allah SWT. Ia menjawab qalbuk (hatimu). Hati seorang mukmin tidak diragukan lagi merupakan tafsir paling baik bagi kitab Allah SWT, dan merupakan jalan paling dekat untuk bisa memahaminya. Ia memberikan langkah-langkah pemahaman tentangnya, sbb: 1) Hendaklah seseorang yang membaca Al-Qur’an disertai dengan tadabbur (meminijnya) dan khusyu’ (ikut serta hati dengan serius terhadap apa yang dibaca); 2) memohon ilham dan petunjuk kebenaran kepada Allah, agar dengan mudah menangkap kandungan setiap ayat yang dibacanya; 3) melengkapi pengetahuan tentang sirah Nabi SAW, yang salah satunya bisa diperoleh melalui asbab al-nuzul dan ikatan turunnya dengan peristiwa yang sedang berlangsung; 4) bila membaca kitab tafsir, berhentilah pada makna lafazh yang terasa pas, atau susunan yang dirasakan tersembunyi maknanya, atau mohon tambahan kecerdasan yang bisa menentukan pemahaman yang sahih terhadap kitab Allah. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah itu, akan mem-bantu pemahaman yang bisa memancarkan cahaya yang datang dari lubuk hati.
Muhammad ‘Abduh berwasiat kepada sebagian murid-muridnya, sebagai berikut: a) Dawamkanlah membaca Al-Qur’an itu; b) fahami oleh kamu segala perintah, larangan, nasihat dan ibadah-ibadahnya, sebagai mana Al-Qur’an ditila-wahkan pada saat diturunkannya; c) hati-hatilah terhadap pan-dangan berbagai penafsiran kecuali hanya untuk memahami maksud ungkapan bahasa Arab yang asing darimu, atau untuk mengetahui kaitan satuan lafazh dengan lafazh lainnya yang hubungan di antara keduanya terlihat samar-samar; 4) berpe-ganglah kepada apa yang Al-Qur’an arahkan untuk diri kamu; dan 5) libatkan dirimu atas apa yang dikehendaki Al-Qur’an itu.
Al-Syaikh Hasan al-Banna dalam mengakhiri bahasannya mengungkapkan bahwa orang yang mengambil langkah-langkah atau cara-cara di atas akan menemukan suatu penga-ruh dalam dirinya, berupa kekuatan pemahaman karena kete-nangannya, dan cahaya yang menyinari kehidupannya di dunia ini maupun di akhirat nanti, insya Allah.
Demikian pula Muhammad Iqbal dalam salah satu penga-laman spiritualnya, mengungkapkan: yang paling mengagum-kan selama hidupku adalah nasihat ayahku kepadaku. Ia berkata: yâ bunayya! iqra’ al-Qur’an kaannahu nazzala ‘alayka (Hai anakku! Bacalah Al-Qur’an itu seolah-olah ia diturunkan kepada mu) .
Berdasarkan beberapa arahan dalam memahami Al-Qur’an sebagaimana dinyatakan di atas, adalah tepat sekali bila yang dimaksud hatimu (qalbuk) dalam jawaban itu adalah hati taqwa dan nurani seorang pembaca secara bersamaan. Ibn Taimiyah dalam Ushûl al-Fiqh-nya, mengajukan suatu kaidah tentang hati taqwa ini, berkaitan dengan posisinya dengan perolehan kebenaran, sebagai berikut: al-qalb al-ma’muru bi al-taqwa idza rajaha bi mujarradi ra’yihi fa huwa tarjihun syar’iyyun (hati yang senantiasa dimakmurkan dengan ketaqwaan apabila menseleksi sesuatu yang mana yang paling baik dengan tanpa melibatkan rationya, maka kekuatannya itu seperti kekuatan yang diperoleh secara syar’iy).
Hubungan berfikir manhaji dan ‘irfani dengan langkah-langkah tersebut adalah sangat dekat, bahkan ketidak mungki-nan berfikir tentang keberagamaan, bisa dilakukan seseorang melalui cara keduanya itu, bila hati dan nurani orang tersebut tidak terlibat. Ketidak mungkinan tersebut dipertimbangkan beberapa hal berikut: a) Ciri khas berfikir manhaji adalah: (1) komprehenshif, dari pemikiran awal sampai pencapaian tujuan akhir; (2) komitmen yang jelas terhadap instrumen-instrumen formal yang perlu dilalui; (3) perumusan sasaran yang perlu dicapai pada setiap instrumen formal; dan (4) tujuan akhir merupakan komulasi dari pencapaian setiap sasaran dalam instrumen formal. b) Ciri khas berfikir berfikir ‘Irfani, adalah: (1) substantif; (2) aspek batin dari setiap aturan formal sangat diperhatikan, guna membangun spirit; (3) meminij qsetiap aturan formal itu seimbang dengan capaian batinnya (religious experience), agar sasaran dan tujuan akhir bisa dicapainya secara seimbang pula di antara lahir maupun batin, individu maupun kolektif.
Bila demikian, maka berbagai metodologi berfikir yang berkembang saat ini, dipertimbangkan sebagai bahan banding-an; bukan sebagai acuan utama. Pertimbangan diambil, ter-utama yang berkaitan dengan aspek-aspek pemikiaran tentang sunnatullah/hukum-hukum Tuhan yang ada di alam raya. Dengan demikian, kemandirian berfikir dan bertindak dari seorang muslim dan umatnya, akan tampak tegak di atas kepri-badiannya, bila disandingkan dengan umat yang selainnya. Bagaimanapun juga ikhtiar yang dilakukan, bila masih tetap acuan utama dan pertamanya, adalah metodologi asing, maka selamanya umat akan tertinggal jauh, karena kreastivitas (ibtikary) dan inovasi (tahditsi) tidak tumbuh terlatih. Fikiran umat terus menerus berada dan rela dalam produk berfikir nomor dua. Akan lebih baik, bila fikiran luar itu, dijadikan anak tangga bagi seseorang yang akan dan sedang belajar, bukan acuan selamanya.
Dalam berfikir keagamaan dengan pola syir‘ah, yang telah baku, seperti dalam kitab-kitab fiqh pada umumnya, berfikir manhaji dan ‘irfani tidak akan ditemukan, kecuali bersifat personal. Hal ini bukan tidak ada atau belum ada, tetapi yang sudah adapun dan disusun para ulama, sepeti kitab Ihya ‘Ulum al-Din karya al-Ghazali, tidak dikaji berdasarkan unity of methodology, tetapi berdasarkan pola syir‘ah. Karena itu, kitab ini lebih dikesani oleh masyarakat muslim, sebagai kitab tasawwuf, daripada kitab fiqhnya. Demikian pula literatur lain-nya seperti karya Ibn Taimiyah, lebih dominan ditangkap pemikiran formalnya daripada pemikiran substantif dari setiap karya-karyanya itu.
E. Implementasi Pemikiran Manhaji dan ‘Irfani dalam Ibadah dan Muamalah.
Yang perlu dicatat lebih awal, adalah tidak ada satu ajaran ibadat dan muamalah pun dalam syari’at Islam yang lepas dari perhatiannya terhadap alam sekitarnya. Karena itu, tiga standar hubungan yang perlu ada dalam setiap kehidupan ini adalah: 1) habl min Allah; 2) habl min al-nas; dan 3) al- ‘alam.
Wahbah al-Zuhaily (al-Tafsir al-Munir: V-VI/102-103) ketika menjelaskan Q.S. al-Maidah: 6; tentang syari’at ber-wudlu untuk menyatakan bahwa terdapat dua perjanjian pada ayat ini dan ayat sebelumnya, yaitu: 1) Perjanjian ketuhanan (‘Ahd al-Rubûbiyyah); dan 2) perjanjian ketaatan (‘Ahd al-Thâ‘ah).[36] Kedua perjanjian ini, baru akan berwujud dan terpelihara dengan baik, bila terkait dengan dipeliharanya ketiga standar hubungan di atas secara bersamaan.
Berdasarkan pola fikir manhaji dan ‘irfani, tidak cukup pelaksanaan thaharah, hanya sebatas berpegang pada ayat itu, yang diperoleh berdasarkan kaidah kebahasaan dan kaidah syari’at yang baku, tetapi perlu sampai pada bagaimana tujuan akhir dari thaharah itu, yaitu suci dari lahir sampai batin (min thaharah al-jism ila thaharah al-qulûb). Al-Shan‘ani (Subul al-Salâm: I/56) menjelaskan ketika menerangkan hadis tentang bacaan persaksian setelah berwudlu: asyhadu an lâ ilâha illallah wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluhu (HR Muslim dari ‘Umar Ibn al-Khaththab), dihu-bungkan dengan Q.S. al-Baqarah: 222; inna Allah yuhibbu al-tawwâbîna wa yuhibb al-mutathahhirîn. Hubungan ini menun-jukkan bagaimana dari berwudlu yang serba zhahir (air, anggota wudlu, dan bacaan setelahnya) itu, bisa sampai pada kesucian batin orang yang berwudlu itu, yaitu orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci hati. Hal ini tidak akan bisa diperoleh kecuali memahami mediumnya, yaitu hati (qulûb) yang bisa memahami realitas (qulûbun yafqahûna biha); bukan hati yang tersumbat (qulûbun lâ yafqahûna, fi qulûbihim ghisyâwah).
Apa yang mesti dipahami hati itu, selain dari dalil, kaifiyah dan alat berwudlu adalah pemahaman terhadap eksis-tensi air, tanah dan indra, serta hubungan di antara semuanya; juga memaknai setiap realitas sebagai alat bertaharah dan indra sebagai anggota tubuh, yang dibasuh dan disapu ketika berwudlu dan bertayammum. Kaidah yang dipakainya adalah kaidah penciptaan (QKh). Namun, informasi tentang QKh ini juga banyak diperoleh dalam Al-Qur’an. Untuk bagian yang terakhir ini, kaidah yang digunakannya secara normatif melalui QL juga, sebagai lanjutan dan perluasan studi fiqh dari yang ada sekarang. Studi lanjutan dan perluasan bahasan tersebut sebagai berikut:
a. Q.S. al-Anfal: 11; memberikan penjelasan tentang eksis-tensi air bagi kehidupan yang relevan dengan sasaran ber-wudlu itu. Terdapat empat fungsi air dalam ayat itu dan sekaligus sebagai indicator sasaran yang perlu dicapai dari sebab berwudlu itu, baik bagi kehidupan pribadi maupun bagi kehidupan bersama, terutama dalam membangun kesatuan uamt (ummah wâhidah), sebagai berikut: 1) li yuthahhirakum bih (untuk mensucikan diri kamu sekalian itu dari kotoran, najis dan hadats); 2) yudzhiba ‘ankum rijza al-syaythân (menghilangkan kamu jauh dari gang-guan syetan); 3) li yarbitha ‘alâ qulûbikum (mengikatkan hati-hati di antara kamu sekalian); dan 4) yutsabbita bihi al-aqdâm (meneguhkan pendirian).
b. Q.S. al-Baqarah: 21 ; Q.S. Qaf: 9-11; fungsi berikutnya, ke 5) nya, diperoleh dari pemaknaan hubungan tanah dengan air. Ketika tanah tersirami air karena hujan atau lainnya. Dalam ayat itu dinyatakan: al-ladzî ja‘ala lakum al-ardha firâsyan wa al-samâ’a binâan wa anzala mina al-samâi mâan fa akhraja bihi min al-tsamarâti rizqan lakum (Tuhan yang menjadikan bagi kamu sekalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan; dan Dia menurun-kan air hujan dari langit, dengan sebab (air hujan) nya itu, lalu Allah mengeluarkan dari bumi itu berbagai buah-buahan sebagai rizqi bagi kamu sekalian. Ketika air bertemu dengan tanah, maka hukum kesuburan tanah akan terjadi, dan tanah akan menumbuhkan berbagai rerum-putan, tanaman dan pepohonan, lalu berbuah dan berbunga. Tegasnya, kehidupan akan ada, oleh sebab air itu. Manusia dan hewan ternak berkembang biak, karena mengambil manfaat dari rerumputan dan buah-buahan itu. Fungsi ke 6) yaitu kehidupan menjadi lestari (Q.S.al-Anbiya: 30). Dengan keenam fungsi itu, mengandung isyarat bagi setiap orang yang anggota badannya tersentuh dengan air wudlu, akan memperoleh enam hal: kesucian badan dan hati; terhindar dari gangguan syetan, kesiapan untuk menyatukan hati, diperoleh kemandirian dan adanya nilai manfaat bagi yang lain dari seseorang yang berwudlu itu, baik ilmu harta maupun tenaga, tidak ada konsep mubazir baginya. Sehingga, kehidupan dan harapan umat bisa tumbuh dan berkembang tanpa beban dan kesulitan. Dikatakan demikian, karena keenam fungsi itu, merupakan hukum asal yang melekat pada air bila bertemu dengan tanah. Demikian juga hukum asal semestinya tetap ada, ketika anggota wudlu yang dibasuh air itu berasal dari tanah, maka hukum asal itu tidak hilang walaupun sudah beralih menjadi wujud lain seperti indra melalui aktivitas berhaharah.
c. Anggota wudlu yang disentuh air itu adalah indra, bukan anggota badan yang lain. Hal itu karena, peran indra seba-gai penentu kedua setelah hati. Sejahtra, selamat, bahagia dan celakanya seseorang atau sekelompok orang selama hidupnya di dunia ini, adalah karena keterpeliharaan indranya.[37] Bila indranya tidak bersih/suci selama berak-tivitasnya, maka ancaman bagi kecelakaan dan kemerana-an hidupnya akan terus mengintainya. Karena itu, akti-vitas indra perlu selamanya dimotivisir oleh kesucian dan kebersihan hati. Hati menjadi penentu kualitas hidup sese-orang, baik ibadah atau muamalahnya. Hadis Nabi SAW riwayat Muttafaq ‘allaih dari ‘Umar Ibn al-Khattab: inna-ma al-a‘mâl bi al-niyyât (segala amal itu ditentukan oleh niyat). Dari hadis itu para ulama fiqh menurunkan sebuah kaidah: al-umûru bi maqâshidihâ (segala urusan itu oleh sebab maqsud hatinya). Terdapat tiga maksud dalam hati manusia itu: fujur/fasad (condong pada kezaliman/rusak); syak (keraguan); dan taqwa/shulh (taat/damai).[38] Dari ketiga maksud hati itu, maka hati taqwa/shulh itu yang bisa mengantarkan seseorang pada maqsud kehidupan yang benar dan selamat. Bila demikian, melalui berwudlu itulah, maka manusia yang bersalah dan telah kotor badan dan jiwanya akan dikembalikan pada fitrahnya. [39]
d. Berdasarkan pertimbangan QKh, bahwa hukum air itu adalah meresap ke dalam tanah, bergerak dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, barulah tanah menampakkan kesuburannya yang akhirnya menumbuhkan berbagai tana-man dan berakhir pada terbangunnya kehidupan, sebagai-mana dikatakan di atas.[40] Namun, sekarang bila diperhati-kan musibah oleh sebab air tersebut banyak terjadi: banjir, longsor ketika musim penghujan tiba, dan krisis air di perkotaan serta berbagai kerusakan bahkan kehidupanpun hilang. Bila diteliti lebih seksama, terjadinya berbagai musibah itu oleh karena hukum meresap bagi air sudah dibatasi orang, karena itu air bergerak terus menuju tempat yang rendah dan menggenang di sana. Itu semua karena keserakahan manusia sendiri, melalui: penebangan hutan secara liar, penembokan halaman rumah dan pengaspalan jalan-jalan diperkotaan yang tidak memperhatikan hukum-hukum yang ada pada air itu, dsb. Bila bangsa Indonesia atau umat, di bumi manapun berada, bila hukum air itu tetap dijaga dan dipertahankan, maka bencana itu tidak akan terjadi. Karena itu mengembalikan kepada karakter-nya yang asli adalah kewajiban kita bersama, terutama bagi umat Islam yang menjadikan air dan tanah itu sebagai alat bersuci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Pengembalian air ke habitatnya itu bukan kewajiban perorangan tetapi kewajiban bersama, terutama arahan dan bimbingan para pemimpin yang menangani urusan publik (pemerintah). Karena itu pemimpin umat perlu memiliki kemampuan membaca realitas dan meminijnya dengan benar sebagaimana sifat seperti disebutkan di atas: Ber-hikmah, ber-‘iffah dan ber-syajâ‘ah.
Dengan demikian, tampaklah hubungan yang simbiosis berjalin berkelindan di antara hati dan indra. Kualitas hati menentukan kualitas kerja indra; sedangkan aktifitas indra yang selektif akan menuntun terbukanya mata hati untuk menerima cahaya Tuhan. Inilah salah satu rahasia ibadah men-jadi kewajiban untuk dilakukan umat manusia selama hidup-nya, tiada lain agar ia selamanya memperoleh bimbingan hidup dari Tuhan.
Penjelasan kasus bertaharah/ber-wudhu di atas, dimaksud-kan hanya sebagai misal saja dalam mengimplementasikan pemikiran manhaji dan ‘irfani. Bila ber-wudlu berangkat dari landasan normatif teks, maka masalah mu‘âmalah dunyâwiyah apapun bisa dikaji melalui kedua pemikiran itu, dengan pem-berangkatan awal dari hukum realitas empiris/konteks, kemu-dian masuk pada kaidah-kaidah normatif teks dengan moral/ akhlak sebagai bingkainya. Karena itu, segala realitas ini dicarikan hubungan-hubungan dan hakikat-hakikatnya, agar bisa dikembalikan kepada hukum asalnya --kesatuan pencip-taan--, bahwa segala realitas ini, diciptakan Tuhan sebagai parsilitas dalam rangka pelaksanaan ibadah umat manusia kepada Nya.
F. Penutup
Akhir dari semua bahasan, tampak jelas adanya persam-bungan yang sangat signifikan di antara cita-cita besar diturun-kannya agama Islam melalui perutusan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi kehidupan masyarakat dunia, dengan kandungan pembentukan rahmat pada bagian-bagian ibadah seperti tarharah ini. Demikian pula hubungan yang sangat simbiosis di antara ibadah-ibadah lainnya yang dikandung Al-Qur’an dan al-Sunnah, dengan hakikat realitas serta hubungan-hubungan yang simbiosis menuju satu kebulatan hukum, yaitu hukum Allah SWT. Namun, semua pencapaian itu perlu diperjuangkan melalui kesungguhan jihad dan ijtihad, pengem-bangan ilmu dan skil, agar optimalisasi pemanfaatan nikmat Tuhan yang diberikan Allah SWT kepada manusia berupa indra, hati dan nurani. Ketiganya dituntut bekerja bersama untuk membukakan segala rahasia kebesaran Allah SWT dan memperlunak rasa ketundukan diri terhadapNya. Dan seperti inilah yang dikatakan sikap ber-tawhid yang benar. Insya Allah .
Daftar Bacaan
Al-Qur’an al-Karim.
‘Ali al-Shabuni, Shafwah al-Tafasir, Dar al-Fikr, Beirut, 1996.
Achmad Charris Zubair, Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan, LESFI, Yogyakarta, 2002.
Abdullahi Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi Syari‘ah, LKiS, Yogyakarta, 1994.
‘Abd al-Razzaq Nawfal, Al-Qur’an wa al-‘Ilm al-Hadits, Dar al-Syu’ab, Kairo, 1982.
Ayat Dimyati, Hadis Arba’in Masalah Aqidah, Mu’amalah dan Akhlak, Marja, Bandung, 2000.
‘Abd al-Wahab Khalaf, ‘Ilmu Ushûl al-Fiqh, Majlis al-A’la, Indonesia,
Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh, Kencana, Jakarta, 2003.
Fak Syari‘ah IAIN Yogya, Ainurrofiq, edt. Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushûl Fiqh Kontemporer, ar-Ruzz, Yigyakarta, 2002.
Fazlur Rahman, Tema Pokok, Pustaka , Bandung, 1995
Fathy Ridlwan, Min Falsafah al-Tasyri’ al-Islami, Maktabah al-‘ilmiyyah, Beirut.
Al-Ghazali, al-Munqid min al-Dlalal, Maktabah Sya’biyyah, Beirut, t.t.
-------------, Al-Mushtasyfa, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.
Hendar Riyadli, edt. Tauhid Ilmu, MTPPI PWM Jawa Barat, Bandung, 2000
Hasan al-Banna, Muqaddamah fi ‘Ilm al-Tafsir,
Ibn Khaldun, Muqaddamah, Dal al-Qalam, Beirut.
Isma’il Razi al-Faruqi, Tauhid, Pustaka, Bandung Jamil Shaliba, al-Mu’jam al-Falsafi, Beirut, 1973.
Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi, Mizan, Bandung , 1999.
Nurcholis Majid, Pintu-pintu Mencari Tuhan, Mizan, Bandung, 1994.
Muhammad Abu Zahrah: Ushûl al-Fiqh, Dar al-Fikr, Beirut, 1958.
Muhammad Khudlari Bik, Ushûl al-Fiqh,
Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi, Markaz al-Tsaqafi, Beirut, 1993.
Osman Bakar, Hierarki Ilmu Membangun Rangka Fikir Islamisasi Ilmu, Mizan, Bandung, 1998.
Rasyid Ridla, al-Manar, t.t.
Raghib al-Ashbahani, Mu’jam Mufradat Alfazh Al-Qur’an, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.
Al-Syatibi, Al-I’tisham, al-Maktabah al-Tujjariyah al-kubra, Mesir, 1332 H.
Al-Shan’ani, Subul al-Salam, Dahlan, Bandung t.t.
Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Dar- Fikr, Beirut,
Biografi penulis:
Ayat Dimyati; lahir di Garut, tanggal 10 Desember tahun 1954; Kegiatan sehari-hari, di samping sebagai pengajar mata kuliah Hadits/‘Ulum al-Hadits pada Fakultas Syari‘ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Spesialisasi dalam bidang hadits, diperoleh dari pendidikannya di S2, bidang Ilmu Hadis pada Pascasarja di lembaga tersebut; dan tahassus Tafsir-Hadits di Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah, Al-Azhar-Kairo (1984-1985). Pelatihan yang telah diikutinya: Peneliti Agama tk. Nasional, Balitbang Agama Depag (1993) dan pelatihan Ilmu Kepustakaan IKIP Bandung (1982). Selain beraktivitas di bidang akademik, penulis juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang sekarang ini sebagai: Ketua PDM Kota Bandung (2000-2005); Ketua MTPPI PWM Jawa Barat (2000-2005); Direktur Pesantren Luhur MTPPI PWM Jawa Barat (sekarang, awal perintisan); dan Anggota Fatwa MUI Jawa Barat. Karya Ilmiyah yang telah ditulisnya: Pengantar Studi Sanad Hadits (1997); Hadis Arba’in Masalah Akidah, Syari‘ah dan Akhlak (2000); Fiqh Rumah Sakit, karya bersama Hendar Riyadi MAg (2000); dan Kapita Selekta tentang Pemikiran Keislaman dan Kemuhammadiyyahan (sedang diedit dalam proses penerbitan).
[1]Idealitas ajaran Islam sebagaimana yang dikandung Al-Qur’an, ter-implementasikan dalam pribadi Rasulullah saw, ketika hidup bersama para sahabatnya, yang relevan dengan pelurusan dan perbaikan terhadap berbagai kondisi dan situasi yang dibutuhkan zamannya. Untuk menyambungkan antara norma ideal yang tetap dengan pola implementasinya dalam realitas kehidupan yang senantiasa berubah ini, diperlukan interpretasi yang berke-lanjutan.
[2]Kata rahmat dalam ayat itu, satu rumpun dengan kata al-Rahmân-al-Rahîm dalam basmalah. Kata bismi merupakan dua kata bi dan ismun. Ismberasal dari kata sumûw yang bermakna tinggi (samawat, jamak). Orang yang mengucapkan basmallah sewaktu memulai perbuatannya, berarti dia telah menempatkan dirinya pada martabat tertinggi; berarti juga meninggikan martabat orang lain pada kedudukannya yang mulya sebagai makhluk Allah, oleh karena amal perbuatannya yang mulya pula. Hal ini sebagaimana yang tercermin dalam wahyu pertama, Q.S. al-‘Alaq: 1-5; dengan isyarat ayat 1 nya, iqra’ bi ism rabbik al-ladzî khalaq. Ism rabbik, merupakan ungkapan pelurusan terhadap tradisi masyarakat Arab jahiliyyah yang pada setiap mengawali perbuatan mereka dengan sebutan ism al-lata wa al-‘uzza (Cf. al-Zamakhsyari dalam al-Kasysyaf). Dengan demikian, rahmatan li al-‘âlamîn merupakan atsar dari nama Tuhan al-Rahmân-al-Rahîm, setelah melewati ucapan lidah seseorang, ditangkap oleh hati dan nuraninya, kemu-dian berbuah pada perbuatannya yang mengandung penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya.
[3]Liberal dan modern, ditujukan bagi para pemikir yang mengacu pada ide-ide dasar Islam yang bersifat substantif-filosofis. Nash-nash yang diru-juknya adalah nash yang bersifat kulliyyat, seperti: keadilan, kejujuran, persamaan, kebenaran, dan nilai-nilai moral universal lainnya. Sedangkan konservatif-tradisional, ditujukan bagi para pemikir yang mengacu pada ide-ide formal praktis empiris orang dahulu. Nash-nash yang dirujuknya adalah nash yang bersifat juziyyah bahkan far’iyyat, seperti: sifat-sifat tertentu tentang agama, umat beragama, kaifiyah beragama dan simbul-simbul formal keagamaan lainya.
[4] ‘Ali al-Shabuni (Shafwah: III/302) memaknai Yang Awal (al-awwalu) dan Yang Akhir (al-akhiru) adalah adanya Allah itu tiada permulaan dan kekekalan Nya tiada akhir. Sedangkan makna Yang Zahir (al-zhahiru) adalah sesuatu yang terjangkau/bisa diukur oleh akal/rasio; dan Yang Batin (al-bathinu) adalah sesuatu di luar jangkauan dan ukuran ratio. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim dan Ahmad diungkapkan: Engkau yang per-tama, bermakna tidak ada sesuatupun sebelummu; dan engkau yang akhir, bermakna tidak ada sesuatupun setelahmu; engkau yang zhahir, bermakna tidak ada sesuatupun di atasmu karena sangat besarnya; dan engkau yang batin, bermakna tidak ada sesuatupun di bawahmu karena sangat kecilnya..
[5] Jamil Shaliba (Mu’jam Falsafi: II/20) mengungkapkan definisi al-manhaj adalah: al-tharîq al-wâdhih al-mustaqim al-ladzî tashîlu bihi al-ghâyah(jalan yang jelas, lurus, yang menyampaikan pada tujuan) (Cf. Raghib al-Ashbahani: Mufradat: 265). Demikian pula kata syir‘ah/syarî‘ah diartikan sebagai jalan menuju sumber mata air. Bila demikian, maka setiap aturan syari‘ah sebagai suatu kewajiban yang mesti ditaati umat, memiliki tujuan-tujuan spesifik masing-masing. Tujuan dari satuan syari’at itu ber-fungsi sebagai penyangga untuk mencapai tujuan akhir yang bersifat global. Karena itu, masing-masing satuan syari’at bisa dikaji secara manhaji agar muatan-muatan di dalamnya, bisa mengantarkan pada tujuan besar itu. Seperti penjelasan aturan berwudlu; ia bisa dilihat secara syir‘ah, yaitu kaifiyah berwudlu sebagaimana dalam pengetahuan pada umumnya orang-orang; bisa juga dilihat, secara manhaji, yaitu bentangan keseluruhan proses dari fase persiapan sampai akhir kaifiyahnya yaitu harapan agar masuk kelompok orang-orang yang lahir batin (al-mutathahirîn, al-tawâbîn).
[6]Raghib al-Ashbahani (Mufradat: 343) mengkonsepkan ‘Irfani: idrak al-syai’i bi tafakkurin wa tadabburin li atsarihi. Pemaknaan ‘irfani dengan tafakkur dan tadabbur menunjukkan adanya dua unsur yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Tadabbur memiliki akar kata da-ba-ra --- du-bu-ran yang berarti: to make plans (merencana), to manage (mengatur), to organize (mengorganisir) danto engeneer (merekayasa) (Hens Wehr, A Dictionary of Modern .....: 1974/270).
[7] Jamil Shaliba (Mu’jam Falsafy: II/72) mendefinisikan al‘Irfan adalah pengetahuan (ilmu) tentang rahasiah hakikat keagamaan. Pengetahuan ini berada di atas wilayah pengetahuan yang pada umumnya orang-orang mukmin ketahui. Sedangkan al-‘Irfany—pakai ya nisbah--, yaitu pengeta-huan yang tidak mencukupkan pada aspek zahir hakikat keagamaan saja, tetapi menjangkau pada bagian yang paling dalam lagi/aspek batinnya.
[8]Kuntowijoyo (Paradigma Islam: 1999/331) memberi catatan bagai-mana memahami Al-Qur’an itu bebas dari beban-beban atau bias-bias histories, jalannya adalah Al-Qur’an tetap berada dalam ikatan transen-dentalnya. Karena itu, warisan historis berupa karya-karya ulama klasik, hanya dipandang sebagai alat bantu dalam memahami wahyu Allah itu. Ia mengajukan pendekatan analitik terhadap al-Quran agar konsep-konsep normatifnya menjadi empiris dan objektif. Dalam hal ini, al-Qur’an, diperla-kukan sebagai data tentang dokumen pedoman kehidupan dari Tuhan. Ini merupakan postulat teologis dan teoritis sekaligus. Dengan demikian ayat-ayat Al-Qur’an merupakan pernyataan normatif yang harus dianalisis untuk diterjemahkan pada level objektif sebagaimana dalam menganalisa data akan menghasilkan konstruk teoritis yang dinamakan konstruk teoritis Al-Qur’an. Hal ini dimaksudkan untuk membangun realitas berdasarkan paradigma Al-Qur’an.
[9]Abdullahi Ahmed an-Na’im (Dekonstruksi Syari‘ah: 3-21) mengung-kapkan bahwa masalah-masalah public/hukum public Islam di dunia muslim tidak jalan, seperti konsep muamalah yang tertuang dalam fiqh muamalah dan hukum pidana Islam yang menjadi kewajiban pemerintahan. Demikian juga kontradiksi-kontradiksi dalam intrepretasi syari‘ah di antara penegakan kemanusiaan (HAM) dengan legalisasi perbudakan dan pembatasan-pemba-tasan hak-hak perempuan, ketidakseimbangan hak-hak muslim dan non muslim dan hubungan internasional. Oleh sebab itu, ia mengajukan teori naskh yang ditawarkan gurunya Mahmoud Mohamed Toha, bahwa ayat-ayat Makkiyyah yang berkarakter egalitarian dan universal adalah lebih pas ditawarkan untuk kontek sekarang ini (berposisi sebagai nasikh). Sedangkan ayat-ayat Madaniyyah adalah ayat-ayat sektarian yang berposisi sebagai syari‘ah histories (dipandang sebagai mansukh).
[10]Kontowijoyo (Ibid: 1999/283) mengajukan lima program reinterpretasi dalam rangka kontektuaslisasi Islam, meliputi: 1) Pengembangan penafsiran sosial struktural lebih ditekankan dari pada penafsiran individual. Artinya, lebih baik mencari penyebab struktural kenapa hidup mewah dan berlebihan itu muncul dalam sistem social-ekonomi, dari pada mencaci maki orang-orang yang hidup mewah dan berpoya-poya. 2) Mengubah cara berfikir subjektif ke cara berfikir objektif, seperti tujuan berzakat secara subjektif adalah membersihkan harta dan jiwa; diubah menjadi tujuan objektif, yaitu tercapainya kesejahtraan sosial. 3) Mengubah Islam normatif menjadi teoritis, seperti konsep tentang fuqara dan masakin lebih dipahami sebagai orang-orang yang perlu dikasihani daripada memahami konsep kaum fakir dan miskin pada kontek yang lebih riel, factual sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan structural. 4) Mengubah pemahaman yang a histories kepada pemahaman histories. Seperti pemahaman tentang penindasan terhadap kaum bani israil oleh Fir’aun, hanya dipahami pada kontek zaman itu, padahal penindasan itu ada dimana-mana sepanjang zaman 5) Memformulasikan ayat-ayat yang bersifat umum menjadi spesifik dan empiris. Seperti Allah mengecam terhadap sirkulasi kekayaan itu hanya pada orang-orang kaya saja adalah pemahaman normatif dan bersifat umum, dipahami menjadi spesifik dan empiris, menjadi Allah mengecam keras adanya monopoli dan oligopoly dalam kehidupan ekonomi politik.
[11] Cf. Muhammad Abu Zahrah (Ushûl al-Fiqh: 327- 361)
[12]Pemikiran kearah itu sudah dimulai, seperti karya Fakultas Syari‘ah IAIN Jogjakarta: Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushûl Fiqh Kontemporer. Walaupun baru bersifat gagasan, tentative dan sebagai embrio, tetapi merupakan langkah awal pengembangan metodologi istinbath ahkam yang bisa mengakses perkembangan sekarang. Dalam buku itu ditawarkan epistimologi jama‘i denganparadigma alternatifnya Acuan pemikiran penawaran itu merujuk pada pemikiran Al-Jabiri, yaitu Bayani, Burhani dan ‘Irfani. (Madzhab Jogja: 50-53).
[13] Ibid , h. 364 - 377 .
[14]Pembidangan kedua pengetahuan ini dikemukakan oleh al-Ghazali dalam al-Mushtasyfa: I/5; Ibn Khaldun dalam Muqaddimah: 345; hanya istilah yang berbeda di antara keduanya itu.
[15]Achmad Charris Jubeir (Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia: 2002/88-89) menyatakan bahwa sillogisme merupakan logika ilmiyah yang diajukan Aristoteles (384-322 SM) yang fungsinya untuk memaparkan metoda untuk memperoleh pengetahuan. Menurutnya, ilmu merupakan pengetahuan yang benar, pemikiran yang lurus berdasarkan alasan: ilmu memperoleh pengetahuan yang khusus dari pengetahuan yang universal melalui penalaran secara silogistis. Tujuan pengetahuan adalah pembuktian secara lengkap melalui rangkaian sillogisme dimana kesimpulan yang diperoleh tergantung pada premis. Proses ini berlangsung sampai dicapai asas-asas yang tidak dapat dibuktikan secara induktif, sebab asas-asas itu termuat di dalam akal dan harus dibuktikan secara deduktif. Pengetahuan manusia bermula dari serapan-serapan indra, berlangsung dari hal yang khusus ke hal yang umum. Hal yang umum dan universal ini merupakan muara terakhir yang dicapai oleh pemikiran manusia. Hal ini berbeda dengan pengetahuan ke wahyuan (agama), yang datang dari hal yang umum (substantif) ke hal yang khusus, yang bersifat instrumental (syari’at formal). Hal yang bersifat instrumental ini, merupakan jalan yang mesti dilalui guna memperoleh tahapan-tahapan pencapaian antara, menuju sasaran paling akhir, yaitu komulasi dari berbagai pencapaian sasaran antara itu.
[16]Syamsul Anwar (Pengembangan Metode Penelitian Hukm Islam dalam Madzhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushûl Fiqh Kontemporer: 2002/159) mencatat pelapisan norma-norma hukum Islam, meliputi: 1) Nilai-nilai Filosofis/Dasar (al-Qiyâm al-Asâsiyyah); 2) Norma-norma Tengah/ Doktrin-doktrin Umum (al-Ushûl al-Kulliyyat). Norma Tengah ini terbagi dua: al-Qawa’id al-Fiqhiyyah/al-Dawabit al-Fiqhiyyah; dan al-Nazhariyyat al-Fiqhiyyah; dan 3) Peraturan-peraturan hukum Konkrit (al-Ahkam al- Far’iyyat. ‘Abd al-Wahab Khalaf(‘Ilmu Ushûl al-Fiqh: 12-13) membuat klasifikasi cakupan nash sebagai dalil hukum ini, kepada: Kully dan Juz’iy.
[17]Sasaran salat bagi individu mushallin adalah li dzikri (mengingat Ku); dengan berdzikir kepada Allah, ketenangan jiwa akan diperolehnya (tathmainn al-qulub); bagi kehidupan sosial adalah tanha ‘an al-fahsya wa al-munkar (mencegah dari perbuatan keji dan munkar).
[18]Definisi hukum sebelum ada perubahan: khithâb allâhi ta‘âlâ al-muta‘alliq bi af‘â al-mukallaf thalaban aw takhyîran aw wadh‘an; setelah ada perubahan: khithâb allâhi ta‘âlâ al-muta‘alliq bi af‘â al-mukallaf syakhshiyyan aw hukmiyyan, fardan aw jamâ‘atan, thalaban aw takhyîran aw wadh‘an, ‘azîmatan aw rukhshatan, shihhatan aw buthlânan al-ladzî tashilu bihi al-mashâlih al-‘ammah. (Makalah seminar nasional tentang Zakat Lembaga, pada Munas MTPPI PP Muhammadiyah ke 25 di Jakarta pada bulan Juli tahun 2000).
[19]‘Abd al-Razzaq Nawfal (al-Qur’an wa ‘Ilm al-Hadits: 152), mengung-kapkan tentang teori kesatuan penciptaan, bahwa sejak beribu-ribu tahun yang lalu para filosuf mebahas tentang materi, termasuk alam. Bahwa alam ini terdiri dari empat unsur, yaitu air, udara, api dan tanah. Pandangan ini berlangsung sampai tahun 500 SM. Teori itu berkembang setelah 2000 tahun kemudian melalui penelitian William Hanjz bahwa materi itu tersu-sun dari kumpulan atom. Masing-masing benda kumpulan atomnya berbeda-beda banyaknya. Atom merupakan bagian materi yang tidak bisa dipecah lagi, ia sebagai kesatuan wujud. Di dalam atom itu terdapat kekuatan listrik, yang positif dinamakan proton dan yang negatif dikatakan elektron. Kesatuan penciptaan ini juga ada pada manusia, yaitu: nafs wâhidah. Demi-kian juga hubungan positif dan negatif dalam penciptaan manusia dengan konsep zawjaha (Q.S. al-Nisa: 1; Q.S. al-A’raf: 187).
[20]Rasyid Ridla (al-Manar: 80) menjelaskan kandungan makna “kana” dalam ayat itu memiliki tiga kemungkinan: 1) kana dalam kuntum adalah tam (tidak membutuhkan khabar) bermakna bahwa kamu sekalian telah menemu-kan diri kamu sebagai umat yang paling baik; 2) kana dalam kuntum adalah naqish (membutuhkan khabar) bermakna, kamu sekalian dulu sebagai umat paling baik; dan 3) kana bermakna shara (menjadi) yang berarti kamu sekalian menjadi umat paling baik. Pengertian yang ketiga ini adalah paling lemah. Dipandang pengertian kana paling lemah, karena posisi khaira ummah itu terkait dengan kriteria iman dan amar ma‘ruf nahyi munkar; bukan hanya sebatan ucapoan saja saya muslim.
[21]Lihat lima program interpretasi Kuntowijoyo dalam catatan kaki no. 7.
[22]Nurcholis Majid (Pintu-pintu Mencari Tuhan: 1994/232) menyatakan kata primordial di Indonesia sering berkonotasi negative yang berarti sikap tidak rasional, seperti kesukuan, keagamaan, kedaerahan dan kedudukan sosial. Kata itu berasal dari bahasa asing yang salah satu maknanya berkonotasi kurang baik, primitive. Tetapi juga kata itu mempunyai pengertian baik dan fositif, seperti bersifat fundamerntal, asli, dll.
[23]Dalam konsep Al-Jabiri , AR dan Qkh ini dikatakan al-Burhani;
[24]Terdapat dua wilayah sunnatullah yang ada di alam raya ini: a) Sunnatullah yang tetap tidak berubah–ubah. Hukum yang dikandungnya adalah bersifat global, universal dan kulliyyat; dan b) sunnatullah yang sedang berproses terjadi yang senantiasa mengalami perubahan. Hukum yang dikandungnya adalah spesifik, khusus dan juz’iyyat (Cf. Srijanto Prono, Hidup Anda di Tangan Siapa: 21-42).
[25]Bangunan Kaidah Kebahasaan (QL) itu, meliputi: makna mufradat (satuan kata), posisi kata dalam satu ungkapan kalimat sempurna (gramatika bahasa Arab), dalalah-dalalah (penunjukan), ushlub (dialek), dan khitab-khitab (titah-titah) –nya (Cf. Muhammad Abu Zahrah: Ushûl al- Fiqh: 139-182 ; Cf. Khudlari Bik: Ushûl al- Fiqh: 109- 212). Pola keberagaam seka-rang ini di bangaun atas dasar pola studi seperti ini, yaitu formal zahir dan individual. .
[26]‘Abd al-Wahab Khalaf (Ilmu Ushûl al-Fiqh: 12-13) membagi juga wilayah kandungan nash itu kepada kulliyyat (global/substantif), dan juz’iyyat (spesifik/formal). Kulliyyat bersifat tetap, karena memiliki kan-dungan universal dan lebih substantif, seperti ayat-ayat tentang persaudaraan, keadilan dan kejujuran. Sedangkan juz’iyyat bisa berubah karena mengan-dung pilihan–pilihan dan praktis/formal, karena terkait dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Dalam konsep al-Jabiri, ATh dan QL ini dikatakan al-Bayani.
[27] Oleh karena moral/etika itu melekat pada para penghidmat ilmu dan penggunanya, maka tanggung jawab kepemimpinan juga melekat padanya. Artinya, setiap orang memiliki tanggung jawab moral yang seimbang dengan wilayah kepemimpinannya. Berdasarkan isyarat hadis Nabi riwayat Muttafaq ‘alaih, wilayah kepemimpinan itu terbagi pada: 1) Kepemimpinan atas semua manusia/jabatan publik; 2) keemimpinan dalam wilayah keluarga (suami); 3) Kepemimpinan sub keluarga/pemelihara di dalam isi keluarga baik orang atau harta (istri); dan 4) kepemimpinan penerima amanat mengurusi harta. Posisi-posisi itu terkait dengan moral yang disandangnya. Moralitas dalam kepemimpinan ini, terbagi pada tiga bagian: a) moral besar (Grand Morality/GM); b) moral menengah (Middle Morality/MM); dan 3) moral dekat/rendah (Low Morality/LM).
[28]Kuntowijoyo (Paradigma Islam: 1999/327-336)
[29]Cik Hasan Bisri (Model Penelitian Fiqh: I, 2003/53) menggambarkan kerangka hubungan dalil dengan subtansi Fiqh, sebagai berikut:
Dalil
Normatif
Substantif
Fiqh
Dalil Dalil
Empiris Metodologi
Tiga bingkai moralitas: ketuhanan, kemanusiaan dan peradaban, meru-pakan kandungan terdalam dan substantif dari setiap aktivitas manusia (Fiqh Sub-stantif). Bila dimasukkan pada kerangka di atas, maka kerangka hubungan ini baru sampai pada tahap keperluan untuk studi. Karena itu kerangka di atas, dimaksudkan guna menurunkannya pada wilayah oprasional empiris yang memiliki kandungan moral.
[30]Objek studi QKh adalah ayat-ayat kauniyah yang ada di alam raya; sedangkan QL adalah ayat-ayat quraniyah. Pola studi QKh adalah mencari hubungan di antara semua realitas, termasuk aturan ibadah ritual, serta hakikat-hakikatnya (shillah wa haqiqatuh), guna penumbuhan kesadaran sosial dan lingkungan. QKh dengan teknik shillah wa haqiqah), diperguna-kan sebagai alat untuk memahami setiap penciptaan yang ada dalam realitas ini. Beberapa isyarat Al-Qur’an menunjukan bahwa, segala realitas ini meru-pakan kebenaran dari Tuhan (al-haq min rabbihim, Q.S al-Baqarah: 24) yang perlu diminij secara benar pula. Detailnya pengaturan terhadap realitas ini diserahkan Allah kepada manusia. Bila diharapkan dari realitas ini mela-hirkan jaminan-jaminan kehidupan, maka pengaturannya perlu benar pula, bukan sebaliknya. Sedangkan pola studi QL adalah pencarian dalil, kaifiyah dan alat-alat (dalâil, kaifiyah wa adâwat) yang bisa menyempurnakan ibadah ritual itu sebagai simbul keta’atan makhluk terhadap Khaliknya. Dengan demikian, maka ketaatan beribadah formal dilakukan seseorang, bersamaan dengan kesadarannya dalam menjalin hubungan dan pemelihara-an terhadap lingkungannya yang sangat terkait dengan urusan publik. Karena itu pula, dalam hukum umumnya, alam dan lingkungan juga digambarkan dalam Al-Qur’an bersamaan dengan kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan umat manusia.
[31]Dikatakan QKh itu filosofis, karena diperlukan proses pengkajian mendalam dan sistimatis dari masing-masing instrumen secara induksi; kemudian dipeloleh hukum-hukum yang tetap, namun bersifat spesifik dalam naungan hukum universalnya; dikatakan logis karena diperoleh berdasarkan pertimbangan ratio; dan empiris karena teraplikasi dalam kehidupan nyata. Sedangkan QL diproses melalui keimanan; ratio tanpa banyak memberikan pertimbangan, diproses mulai dari hal yang universal sampai hal teknis oprasional ditunjukinya. Bila memperhatikan sifat-sifat nash yang turun secara berangsur-angsur, dari Makkiyyah ke Madaniyyah, maka karakter nash itu akan terlihat kandungannya, meliputi: global/universal (kulliyyat) dan substantif, kemudian spesifik (juziyyat) dan personal.
[32] Fathy Ridlwan (min Falsafah al-Tasyrî‘ al- Islâmi: 1975/41-58), mengemukakan bahwa semua rumusan nash kully atau nash yang menun-jukkan tidak ada nash lain kecuali yang dimaksud adalah makna zahirnya, seperti tentang keesaan Allah SWT, persaudaraan, keadilan dan persamaan; atau nash umum lainnya; atau nash-nash juziyyat setelah menstudi nash-nash juziyyat lainnya yang saling berhubungan secara komprehenshif, merupakan hukum asal, mabadi atau asas. Demikian pula pernyataan al- Syatibi (al- I‘tishâm: II/166-180). Karena nash tersebut, dipandang sebagai hukum asal, mabadi’ dan asas, maka kandungan makna nash-nash juziyyat secara parsial, bila keluar dari makna hukum asal itu--bisa berubah makna formalnya kepada makna lain--, bila nash juziyyat itu berhadapan dengan konteks yang berbeda dari pemaknaan pertama. Oleh sebab itu, dari nash juziyyat inilah terjadinya ikhtilaf dikalangan umat, bukan dari nash kulyyatnya, demikian kata al-Syatibi (Ibid: 167). Karena itu ikhtilaf dalam juziyyat itu bukan merupakan satu kesalahan, bahkan suatu kemestian adanya.
[33]AC Zubeir (Dimensi Etik...: 18) menjelaskan fungsi indra kaitannya dengan ilmu pengetahuan adalah sebagai pintu gerbang pertama pengetahuan manusia. Nurani adalah potensi kemanusiaan untuk memahami martabat manusia sebagai makhluk spiritual , pemahaman atas kebaikan, keburukan dan keadilan, pemahaman atas moralitas manusia. Pengertian nurani seperti itu bila merujuk pada Al-Qur’an dan al-Hadis adalah bermakna qalb. Q.S. al-Syams: 4-5; menjelaskan dua potensi dalam nafs (qalb/hati) ini, yaitu: fujur dan taqwa; dan HR Muttafaq ‘alayh dari Nu’man Ibn Basyir, mengisyaratkan terdapat dua jenis qalb (hati), yaitu: shulh (baik) dan fasad (rusak); bahkan dalam hadis lainnya terdapat juga sifat syak (ragu) atas kebenaran atau kesalahan. Al-Ghazali (al-Munqîdz min al- Dhalâl: 124) mengumpamakan al-qalb dengan cermin yang bisa menangkap berbagai gambar yang disimpan Allah pada diri manusia. Demikian juga di Lawh al-Mahfûzh terdapat juga cermin yang bisa menangkap berbagai realitas. Bila qalb manusia itu bersih dari kotoran syahwah duniawi, maka ia akan jelas pula menangkap dan membaca segala informasi realitas sebagai bahan ilmu pengetahuan, yang dikirim oleh cermin Lawh Mahfûzh ke hati setiap orang itu. Sedangkan makna Nurani dalam arti Lubb (al-albâb, jamak); mengacu pada Q.S. Ali ‘Imran: 190-191; memiliki potensi untuk berdzikir dan berfikir yang sama-sama menuju pada kesimpulan ke Maha Sucian Tuhan. Al-Ghazali (al-Munqîdz min al-Dhalâl: 124) mengumpamakan al-qalb dengan cermin yang bisa menangkap berbagai gambar yang disimpan Allah pada diri manusia. Demikian juga di Lawh al-Mahfûzh terdapat juga cermin yang bisa menangkap berbagai realitas. Bila qalb manusia itu bersih dari kotoran syahwat duniawi, maka ia akan jelas dan terang pula menangkap dan membaca kebanaran segala informasi tentang realitas sebagai bahan ilmu pengetahuan, yang dikirim oleh cermin Lawh Mahfûzh ke hati setiap orang itu. Dalam konsep al-Jabiri, dimensi akhlak/moral ini dikatakan al-‘Irfani.
[34]Bila pada kenyataannya masih tetap terjadi ikhtilaf/berbeda dalam kesimpulan akhir yang tidak mendukung subtansinya, maka kesalahan niscaya terjadi pada kesimpulan yang ditemukan pada bagian-bagiannya yang diproduk manusia, bukan pada hukum asalnya. Dengan demikian, maka mempertemukan setiap yang ikhtilaf itu termasuk ikhtilaf dalam keilmuan, perlu berlanjut walaupun pindah generasi (Cf. Osman Bakar, Hierarki Ilmu: 11). Yang dimaksud ikhtilaf di sini, menyangkut ikhtilaf dalam subtansinya, bukan pada proses kerja, medium dan sumbernya. Bahkan ikhtilaf pada bagian akhir ini merupakan satu kelogisan. Seperti: memelihara kesehatan badan merupakan kewajiban agama. Ilmu Kedokteran menemukan teknologi oprasi mata katarak. Orang yang sakit mata katarak bisa baik lagi pengli-hatannya setelah melalui oprasi itu, maka temuan dalam Ilmu Kedokteran itu, relevan dengan cita-cita ajaran agama dalam pemelihara kesehatan umatnya.
[35]Masing-masing dari keenam pertanyaan itu, terkait dengan standar tingkatan kemampuan penguasaan keilmuan seseorang, bahkan umat, dari tingkatan yang sangat dasar sampai pada tingkat kemandiriannya, sekaligus sikap dan pengamalannya secara bersamaan.
[36]Kedua konsep ini dijadikan acuan awal dalam kerangka membangun konsep unity of methodology. Yang kemudian dikembangkan menjadi konsep keilmuan yang teraplikasikan dalam dua kaidah: QKh dan QL sebagaimana dikemukakan di atas.
[37]Hadis nabi SAW riwayat Bukhari, Abu Daud dan al-Nasai dari.Abdullah Ibn Umar dari nabi SAW berkata: al-muslimu man salima al-muslimûna min lisâni wa yadihi wa al-muhâjiru man hâjara ‘an nahâ Allahu ‘anhu.(Orang Islam adalah orang-orang muslim yang selamat lidah dan tangannya, dan orang yang muhajir adalah orang yang berhijrah dari apa yang Allah SWT telah melarangnya). Karena itu berfikir manhaji tidak bisa keluar dari berfikir syir‘ah sebagai tahap awal dan itu merupakan kesempurnaan agama Islam.
[38]Q.S. al-Syams: 4-5; Hr. Bukhari dari Nu’man Ibn Basyir tentang halal bayyin dan haram bayyin. Bakna bayyin di sana adalah diketahui sampai detailannya, sebagaimana dikemukakan di atas.
[39]Nurcholis Majid (Pintu-pintu Mencari Tuhan: 186-187) menyatakan bahwa agama memerintahkan dan mendorong kita untuk berbuat dan ber-amal salih yang akan membawa kebaikan bagi orang lain dalam masyara-kat dan menghantarkan pada keridlaan Ilahi di akhirat. Perintah dan dorongan berbuat baik itu dari Allah SWT melalui para utusan-Nya. Sungguh bahwa berbuat baik itu merupakan bakat primordial manusia yang bersumber dari hati nurani karena adanya fitrah. Karena itu, berbuat baik adalah sesuatu yang natural sebagai perpanjangan nalurinya sendiri.
[40] Karakter air seperti ini diceritakan juga dalam Q.S. al-Hajj: 5.
Tags: